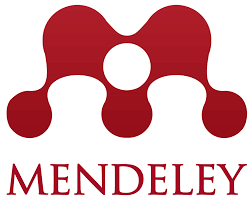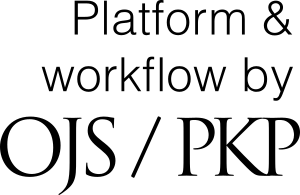Narasi Komodifikasi dan Relasi Kuasa pada Kumpulan Cerpen “Nelayan Itu Berhenti Melaut” Karya Safar Banggai
DOI:
https://doi.org/10.15408/dialektika.v12i1.42343Keywords:
komodifikasi, masyarakat laut, objektifikasi, relasi kuasa.Abstract
Semenjak digaungkannya kebijakan “kembali ke laut”, ada banyak hal yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia untuk mendulang pendapatan dari sumber daya laut Indonesia, termasuk potensi pariwisatanya. Dalam pelaksanaan program tersebut, ada beberapa isu yang muncul terkait kesejahteraan dari masyarakat maritim/laut itu sendiri. Dalam kumpulan cerpen “Nelayan itu Berhenti Melaut” karya Safar Banggai, isu-isu tersebut diangkat sebagai narasi utama. Isu tentang objektifikasi masyarakat laut yang berkait dengan komodifikasi laut dan perkampungannya disampaikan dengan penyajian yang menarik, dengan menempatkan masyarakat pada relasi kuasa yang ironis. Oleh karena itu, artikel ini akan mencoba untuk membedah isu tentang narasi komodifikasi dan relasi kuasa dalam beberapa cerpen di kumpulan cerpen tersebut. Analisis dalam artikel ini akan menggunakan pendekatan sosiologis, dengan meminjam teori-teori kritis yang berpusat pada konsep komodifikasi dan relasi-kuasa. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa masyarakat laut yang dinarasikan pada beberapa cerpen terikat pada relasi kuasa yang membuat suara-suara mereka redup dan membuat mereka tereifikasi sebagai objek. Bentuk komodifikasi tersebut tidak hanya terbaca pada bentuk objektifikasi masyarakat dan perkampungannya yang dianggap eksotik saja, tetapi juga praktik-praktik sosial budaya yang berubah karena tradisi masyarakat yang tergadaikan.
Kata kunci: komodifikasi, masyarakat laut, objektifikasi, relasi kuasa.
References
DAFTAR PUSTAKA:
Banggai, Safar. (2019). Nelayan Itu Berhenti Melaut. Yogyakarta: Pojok Cerpen.
Barker, Chris. (2014). Kamus Kajian Budaya. Yogyakarta: Kanisius
___________. (2005). Cultural Studies, Teori dan Praktik (terj.). Yogyakarta: Bentang Pustaka.
Barthes, Roland. (2012). Mythologies. Farrar, Straus, and Giroux.
Eagleton, Terry. (2000). The Idea of Culture. USA: Blackwell Publishing.
Hall, Stuart. (1997). “The Work of Representation” dalam Stuart Hall (ed.). 1997. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage Publication.
Ibrahim, Idi Subandhy & Bachruddin Ali Akhmad. (2014). Komunikasi dan Komodifikasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kharisma, Talitha Lulu. (2019). “Nilai Karakter Cinta Lingkungan pada Novel Mata dan Manusia Laut karaya Okky Madasari.” Prosiding SENASBASA (seminar Nasional Bahasa dan Sastra) hlm. 991-999.
Kurnia, Erika. (2019). “Masyarakat Indonesia Timur Belum Berdaulat atas Kekayaan Alamnya”. https://www.kompas.id/baca/utama/2019/08/18/masyarakat-indonesia-timur-perlu-naikkan-nilai-tawar. Kompas.id. 18 Agustus 2019. Pukul 21.44.
Luxemburg, Jan van, Williem G Westeijn, dan Mieke Ball. (1984). Pengantar Ilmu Sastra. Jakarta: Gramedia.
Mike Wijaya Saragih, & Teguh Prasetyo. (2023). “Representasi Identitas Masyarakat Laut dalam Kumpulan Cerita Pendek Nelayan Itu Berhenti Melaut”. Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra, 9(2), 1189-1204. https://doi.org/10.30605/onoma.v9i2.2958
Mosco, Vincent. (2009). The Political Economy of Communicaton, edisi ke-2. London and New York: Sage.
Mustikawati, Aquari. (2019). “Eksploitasi Sumber Daya Alam: Kajian Ekologi Budaya dalam Dua Cerpen Kalimantan Timur”. Jurnal Informatika UPGRIS Vol. 5, No. 2 Desember
Soetomo, Greg. (2003). Krisis Seni Krisis Kesadaran. Yogyakarta: Kanisius
T Knijn, dan I Ostner. (2002). “Commodification and de-Commodification” dalam Barbara Hobson, dkk (ed.). Contested Concept in Gender and Social Politic. Edward Edgar Publishing.